Intro
Pada tahun 2013, Paus Fransiskus mencopot seorang uskup dari tugas episkopalnya karena membuat skandal gereja di Jerman dengan membangun tempat tinggal mewah senilai $34 juta dengan menggunakan dana gereja. Media Jerman menjuluki uskup tersebut sebagai “luxury bishop.” Sejak awal kepausannya, Paus Fransiskus sangat tegas dalam posisinya untuk hidup sederhana dengan membayar tagihan hotelnya sendiri dan memilih sebuah mobil kecil untuk dirinya sendiri— bukannya mobil mewah. Hari ini kita mau belajar tentang pandangan Gereja Katolik tentang materialisme (kemewahan) dan bagaimana seharusnya kita bersikap.
Materialisme
Bagaimana dengan dosa kemewahan dalam hidup kita sendiri? Bukankah “too much” telah menjadi standar yang biasa dan dapat diterima di rumah dan lingkungan sekitar kita? Para filsuf zaman dahulu dan nabi-nabi Israel bersatu dalam mengkritik pertunjukan kekayaan yang berlebihan dan, mulai sejak zaman Plato, istilah “luxury” diterapkan pada sifat buruk ini.
Mereka tidak menentang kepemilikan (possession) loh ya. Namun, mereka berpikir ada garis atau batas di mana manusia tidak boleh pergi keluar dari garis tersebut. Kemewahan berarti keinginan yang berlebihan untuk memiliki dan—seperti yang diilustrasikan oleh kisah uskup yang mewah itu—segala sesuatu bisa menjadi berlebihan. Tapi bukankah kita selalu berlebihan dalam kehidupan kita sehari-hari?
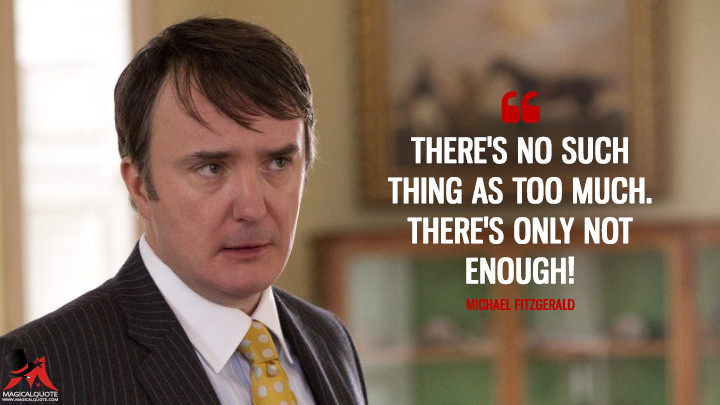
Rasanya kita juga jarang melihat orang Kristiani lainnya menjalankan perintah Yesus untuk meninggalkan semua harta benda. Apakah perintah itu masih relevan? Tidak semua dari kita harus menjadi seperti St. Fransiskus yang meninggalkan semua harta benda dan kekayaannya. Tapi, di sisi lain, kita juga tidak boleh mengabaikan perintah ini. Coba, berapa banyak dari kita yang sering beralasan: “Tidak masalah memiliki harta benda selama kita terlepas darinya (tidak ketergantungan)”. Namun, jika kita benar-benar tidak terikat, maka kita seharusnya bisa membedakan kelebihan (excess) sebagai kemewahan dan menolaknya.
Jadi, di mana batasannya?
Dalam pidatonya, Paus Fransiskus bercanda bahwa seseorang mungkin akan membalas homilinya mengenai “uskup mewah” di atas dengan bertanya: “Jadi, Bapa Paus menyuruh kita untuk menggunakan sepeda kemana-mana?” “Tidak, mobil berguna untuk menyelesaikan hal-hal tertentu, tetapi seseorang tidak perlu “mobil mewah” untuk itu”. Teladan Bapa Paus ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita sebaiknya mendefinisikan kemewahan. Untuk membedakannya, kita perlu mengajukan pertanyaan ini kepada diri sendiri: “Untuk apa harta benda kita ini?”.
Kata ”dosa” berasal dari kata Yunani yang berarti “tidak mengenai sasaran.” Kita hanya dapat mengetahui bahwa kita telah berbuat dosa jika kita mengetahui target yang mau kita tuju. Harta milik kita menurut KGK no. 2402 memiliki dua tujuan: untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga kita dan untuk “memungkinkan solidaritas alami” di antara orang-orang. Kita masuk kategori berlebihan—dan “meleset dari sasaran”—ketika kita menggunakan harta benda untuk menciptakan dan melayani kebutuhan palsu dalam diri kita sendiri dan untuk mendorong persaingan di antara orang-orang. Itulah sifat buruk kemewahan: kita menginginkan banyak hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Terkadang, mendapatkan hal-hal itu malah memicu kecemburuan dan persaingan dengan orang sekitar kita. Itu adalah sifat buruk karena kita menjadi terbiasa dengannya; seolah-olah kita terbiasa mengejar hal-hal yang lebih mewah bahkan ketika itu jelas tidak perlu dan sebenarnya barang-barang lama kita masih berfungsi dengan baik.
Di benak kita, kita pasti menyadari kebenaran dari pernyataan ini. Mengikuti tren terkini itu melelahkan dan pada akhirnya tidak membawa kita pada kebahagiaan sejati. Hal ini juga sudah dibuktikan oleh banyak penelitian dari ilmuwan sosial. Kelebihan barang dan persaingan materialistis dengan orang lain tidak menghasilkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Tapi tetap saja, sepertinya kita tidak bisa berhenti untuk mengumpulkan semua barang-barang material. Contohnya: selalu upgrade ke iPhone terbaru soalnya kelihatan keren sih!
Memang barang-barang material ini keren. Tapi di sinilah kita menghadapi masalah di zaman sekarang yang tidak pernah dibayangkan oleh para filsuf zaman dulu. Kita memiliki seluruh industri pemasaran (marketing) yang berulang kali meyakinkan kita betapa “ajaib”-nya barang ini dan itu. Kita pun akan menghabiskan lebih banyak uang jika kita percaya dengan “keajaiban” tersebut. Pembuat barang-barang mewah menjelaskan bahwa apa yang mereka jual bukan hanya materi, tetapi juga “perasaan” dan “keinginan untuk merasa istimewa”. Produk mewah seringkali diibaratkan sebagai “mimpi”. Namun, banyak juga yang melihat produk-produk ini bukan hanya sekedar merek, tetapi juga sebuah “agama.”
Dari sudut pandang Katolik, kita juga meyakini bahwa ada keajaiban yang dibawa oleh barang-barang material, dan kata yang kita pakai untuk mendeskripsikannya adalah sakramen. Tetapi tentunya keajaiban ini tidak seperti yang kita bayangkan. Di luar 7 sakramen, para filsuf Katolik juga mengajarkan tentang “sakramental dunia” (sacramental worldview) dimana kita terus-menerus membangun relasi spiritual dengan Tuhan dan sesama lewat barang-barang material yang dipakai di dunia ini. Contoh yang paling gampang adalah saling memberikan hadiah/kado. Sebelum hadiah/kado menjadi objek yang digembar-gemborkan iklan/media sosial untuk mempengaruhi sentimen konsumen, sebenarnya saling memberikan hadiah/kado ini menunjukkan ikatan sosial yang tidak kelihatan dengan sesama kita.
Paus Emeritus Benediktus menulis tentang pengalaman istimewa ketika kita memberikan hadiah/kado di dalam tulisannya tentang ekonomi Katolik. Dia berkata bahwa kita harus berusaha membuat semua interaksi ekonomi kita dengan sesama mengandung unsur “hadiah” di dalamnya, dimana kita memberi dari kelebihan kita untuk membangun relasi dengan manusia lain, dan disinilah barang-barang material ini membawa keajaiban bagi kita. Orang-orang yang mempromosikan kemewahan justru ingin kita berpikir sebaliknya, bahwa barang-barang ini akan membawa keajaiban jika kita pakai untuk diri kita sendiri atau membuat kita diterima dalam kelompok eksklusif/VVIP yang tidak mungkin dimasuki oleh orang-orang yang tidak punya kemewahan ini yang notabene adalah kebanyakan orang di dunia ini.
Efek Covid-19
Pandemi Covid-19 menyadarkan banyak orang bahwa harta benda bukanlah yang terpenting dalam hidup. Semua barang yang kita miliki tidak ada artinya ketika kita terbaring sakit tidak berdaya. Virus Corona tidak pandang bulu, dia bisa menyerang orang kaya dan miskin kapan saja. Walau kita bisa membeli obat ataupun kamar di rumah sakit dengan uang, tetapi hal itu bukan jaminan bahwa kita tetap bisa hidup.
Ketika harta benda tidak bisa menyelamatkan kita, apa yang lalu menjadi harapan kita? Kita berharap ada Tuhan atau sesuatu kekuatan/roh/energi (bagi orang yang tidak percaya Tuhan) yang dapat memusnahkan virus ini dan membuat dunia kembali seperti semula. Kita berharap kita masih diberikan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai dan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai dibandingkan menghabiskan waktu dengan pekerjaan/usaha kita untuk mendapatkan uang dan status.
Juga pandemi mengajarkan bahwa kita tidak bisa selamat sendirian. Ketika kita berusaha bersama-sama agar semua orang selamat, maka barulah kita juga mungkin selamat. Di sini ditekankan pentingnya berbagi untuk kepentingan bersama seperti yang diajarkan oleh Gereja Katolik dari zaman dahulu dan suatu konsep yang sering dikritik oleh dunia sekuler.
Konsep materialisme yang menekankan pentingnya mengumpulkan barang-barang material sebanyak-banyaknya mulai kelihatan korengnya. Tidak ada satupun barang-barang material ini yang dapat kita bawa ketika kita meninggal. Justru hal-hal spiritual yang tidak dapat dipegang dan dilihat adalah yang lebih penting untuk membuat hidup kita di dunia ini lebih berarti sampai ajal datang menjemput.
Efek YOLO dan FOMO
Belakangan ini kita sering mendengar istilah YOLO (You Only Live Once) dan FOMO (Fear of Missing Out) dan secara sadar maupun tidak, kita sudah terpengaruhi oleh prinsip ini. Penganut prinsip YOLO berpikir kalau hidup itu hanya sekali saja. Jadi kalo ada kesempatan, kenapa tidak diambil? Urusan yang lain, bisa belakangan. Contohnya, seperti tiba-tiba membeli tiket pesawat untuk travelling tanpa mempertimbangkan kondisi lainnya. Pokoknya, kalau tiket pesawat lagi diskon dan destinasinya adalah impian kamu, langsung diserbu!
YOLO seolah-olah memberikan gambaran bahwa hanya ada satu kehidupan di bumi ini, dan setelah kita mati, kita akan pergi selamanya. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Tidak ada hukuman untuk kejahatan yang kita lakukan, atau hadiah untuk melakukan kebaikan. Karena tidak ada konsekuensi kekal untuk dosa-dosa kita atau kebaikan yang kita lakukan, sebaiknya kita memanfaatkan hidup ini sebaik-baiknya, hidup di tepi “jurang” karena begitu kita mati kita tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk merasakan kenikmatan hidup ini. Kita tidak perlu khawatir tentang masa depan umat manusia karena tidak ada yang namanya masa depan. Lagipula ini bukan masalah kita. Generasi berikutnya harus menghadapinya sama seperti kita menghadapi tantangan kita saat ini.
Lalu bagi orang-orang yang FOMO, kehidupannya penuh dengan rasa gengsi dan kecenderungan ingin mengikuti tren-tren di luar sana, terutama sejak adanya media sosial. Contohnya, ketika melihat update soal Hypebeast kalau chunky sneakers jadi tren di tahun 2020, dan juga didukung oleh teman-teman sekitar yang juga ikutan memakai chunky sneakers ke berbagai acara, langsung ikutan memborong deh. Kita ikutan membeli karena takut ketinggalan, padahal belum tentu kita suka dengan gaya tersebut.
Obsesi kita untuk selalu mengkonsumsi dan menikmati hal-hal material di zaman sekarang gara-gara YOLO maupun FOMO tidak akan ada habisnya. Mungkin kita merasa bahagia dengan hal-hal material ini, dengan pujian yang kita terima dari orang-orang sekitar kita, dan dengan mengikuti tren terkini supaya tidak dicap ketinggalan zaman— tapi apakah kita sudah mempersiapkan untuk kebahagiaan kita bersama Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan kita setelah di dunia ini, apakah kita sudah siap?
Kesimpulan
Kita dapat melawan konsep materialisme tidak dengan merendahkan hal-hal material dan/atau sebaliknya meninggikan hal-hal yang spiritual. Iman Katolik adalah sakramental, menggunakan hal-hal yang fisikal/material untuk mendapatkan hal-hal yang spiritual/kekal. Inkarnasi Kristus menjadi manusia menunjukkan bahwa hal-hal yang material pun bagus adanya dan dapat membawa keselamatan, yang mungkin banyak orang tidak pernah berpikir seperti itu.
Contoh yang paling sempurna kita dapatkan lewat Kristus sendiri yang memberikan diri-Nya dalam rupa hosti dan anggur, yang kita rayakan dalam Misa dan juga ketika melakukan adorasi Sakramen Maha Kudus. Marilah kita semakin menghargai kekayaan yang ditawarkan oleh Gereja Katolik lewat sakramen-sakramen dan mendedikasikan hidup kita untuk melayani dan membangun persahabatan dengan banyak orang yang kita percaya diciptakan serupa dan secitra dengan Allah. Kita boleh mengumpulkan hal-hal material, tetapi gunakanlah ini untuk membantu sesama, membangun suatu komunitas, dan khususnya untuk membangun keluarga.
Pertanyaan Sharing
- Sharingkan 1 barang yang paling kita sukai dan apa reaksi kita jika diminta memberikan barang itu kepada orang lain.
- Sharingkan apa barang material yang kamu sedang/sering incar-incar. Dan setelah mengikuti CG hari ini, apakah kamu merasa sudah memiliki ketergantungan terhadap barang atau merek tersebut?
- Media sosial menjadi ajang untuk pamer kemewahan dan terkadang membuat kita merasa FOMO (Fear of Missing Out). Apa pendapat/pengalamanmu tentang hal ini? Sharingkan.
Bonus Point: Donasikan barang-barang yang masih layak kepada orang-orang lain atau komunitas yang lebih membutuhkan!
Referensi
- https://www.google.com/amp/s/aleteia.org/2022/01/27/materialism-again-really/amp
- https://uscatholic.org/articles/201603/the-invisible-bonds-of-materialism/
- https://m.tribunnews.com/amp/lifestyle/2020/04/07/yolo-fomo-mungkin-bikin-remaja-boros-tapi-ada-keuntungan-yang-bisa-didapat-lho-ini-prinsipnya?page=4
